Pink Tax, Diskriminasi Harga Berbasis Gender
Sekaring Ratri Adaninggar
|
Monday, 20 July 2020
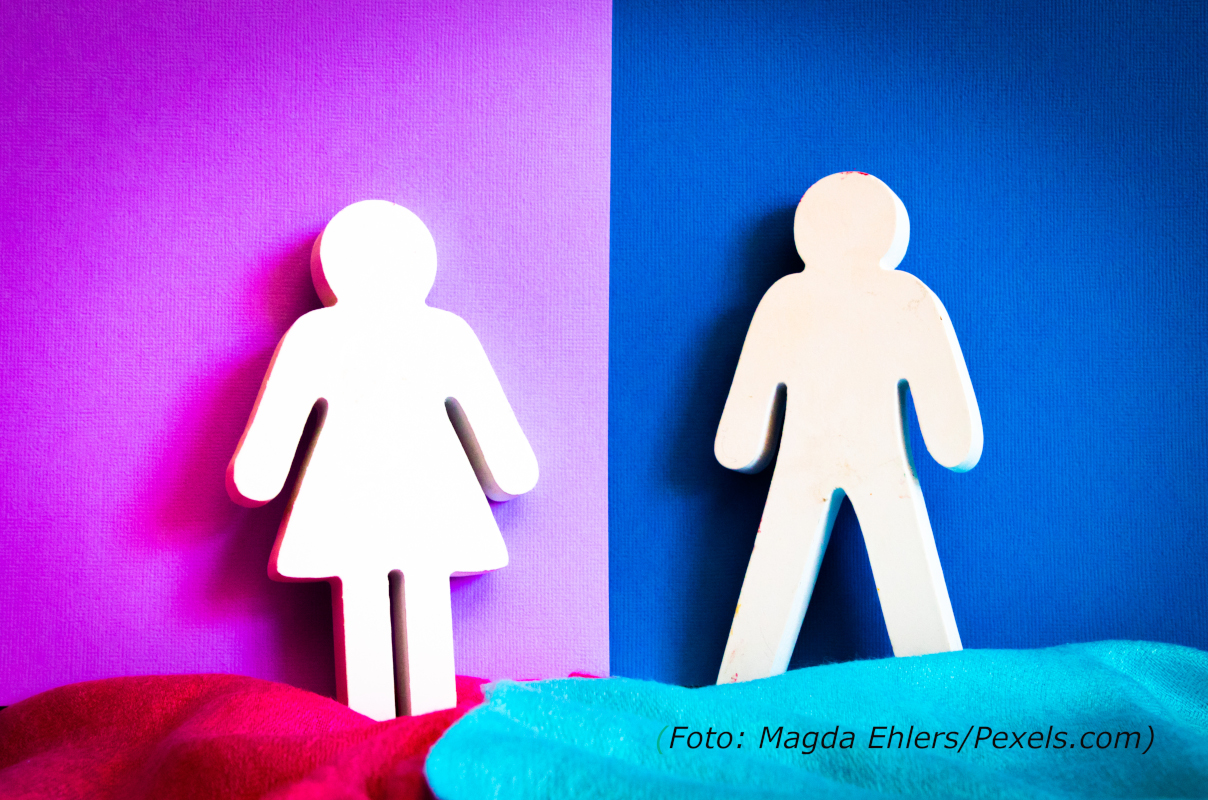
Jenis pajak di dunia beragam. Mulai dari yang paling aneh sampai yang cukup rasional. Bahkan, ada juga yang memantik isu-isu sensitif seperti kesetaraan gender. Misalnya, pajak merah muda (pink tax) atau yang sering juga disebut pajak gender. Konsep pajak berbasis gender ini sampai sekarang masih menjadi kontroversi di sejumlah negara.
Pink tax sejatinya merupakan istilah yang sering dikaitkan dengan diskriminasi harga berdasarkan gender. Gampangnya, pink tax mengacu pada selisih harga lebih mahal yang harus dibayar mayoritas perempuan dibandingkan pria ketika membeli barang maupun jasa. Kenapa pink? Karena warna ini dianggap paling mewakili kaum hawa, meskipun kenyataannya tidak selalu demikian.
Pink merupakan salah satu warna yang memiliki sejarah panjang. Ternyata, pink telah dikonotasikan sebagai warna feminin sejak era Perang Dunia II. Terutama, setelah mantan ibu negara Amerika Serikat (AS), Mamie Eisenhower popular dengan obsesinya terhadap warna pink, hingga mendapat julukan sebagai mother of pink. Sebagai ibu negara, apapun yang dilakukan Eisenhower pasti menjadi sorotan publik.
Memasuki era 1980-an, perusahaan-perusahaan di Amerika mulai menciptakan tren warna pink ini untuk strategi pemasaran. Mereka menggembar-gemborkan bahwa warna pink untuk perempuan dan biru untuk laki-laki. Mulai dari mainan, baju, perabot, peralatan sekolah hingga atribut bayi dibuat dengan dua warna tersebut sebagai identitas pembeda. Tidak heran, generasi yang lahir pada tahun 1980-an ke atas memiliki pola pikir pink adalah warna perempuan. Akhirnya, hingga saat ini warna pink menjadi identik dengan warna yang feminin.
Stereotip
Padahal, jauh sebelum mother of pink menjadi trendsetter, pink justru diidentikan sebagai warna maskulin. Mengutip Tirto.id, arsitektur terkenal asal Italia Leon Battista Alberti pada 1435 memperkenalkan teori warna (color theory). Melalui tulisannya "De Pictura" (terjemahan bahasa Inggris “On Painting” oleh Jhon R Spencer, 1970), dia mendeskripsikan pink sebagai warna maskulin. Pertimbangannya adalah karena warna tersebut sangat tegas dan keras sehingga cocok dengan jiwa pria. Tidak hanya itu, unsur warna pink juga dianggap cocok dengan warna coklat, yang kebetulan mendekati warna rambut kebanyakan pria di barat.
Sebaliknya, biru justru dianggap sebagai warna yang feminin pada abad 18 hingga 19. Adalah Jhon Gage, yang dalam tulisannya Color in Western Art: An Issue mengklasifikasikan kasta sosial berbasis warna: emas (gold) mewakili warna kebangsawanan; merah (red) mewakili orang bebas (freemen); dan biru (blue) mewakili para budak. Pada era tersebut, mayoritas budak adalah wanita, maka biru pun melekat sebagai warna yang feminin.
Masih dari sumber yang sama, Tirto.id, pembuktian stereotip warna berbasis gender tersebut juga dilakukan oleh Profesor Jo B. Paoletti dari Universitas Maryland, Amerika Serikat. Melalui situs resminya pinkisforboys.org, selama 30 tahun Paoletti meneliti warna kostum yang digunakan oleh anak-anak di Amerika Serikat pada abad 18 hingga 19. Dalam bukunya Pink and Blue: Telling the Girls and the Boys in America, dia menjelaskan bahwa pada abad 18, hampir semua pakaian anak-anak panti asuhan di Eropa dominan dengan warna pink. Sementara di Amerika Serikat pada era 1818 hingga 1882, warna-warna cerah seperti pink, putih, dan ungu umumnya digunakan oleh para pria.
Diskriminasi Gender
Pada 2015, diskriminasi harga berbasis gender atau pink tax sempat menjadi pembicaraan hangat pasca Departemen Urusan Konsumen Kota New York (New York City Department of Consumer Affairs), mempublikasikan hasil studinya yang terkait disparitas harga antara produk perempuan dan laki-laki. Studi berjudul "From Cradle to Cane: The Cost of Being a Female Consumer" itu menemukan bahwa rata-rata produk perempuan harganya 7% lebih mahal dibanding produk laki-laki untuk jenis produk yang serupa atau bahkan identik.
Studi tersebut mencatat, dari total 794 produk yang diteliti, ada beberapa produk yang disparitas harganya cukup significant antara produk perempuan dan laki-laki. Produk-produk tersebut antara lain:
* 7% lebih mahal untuk mainan dan aksesoris
* 4% lebih mahal untuk pakaian anak-anak
* 8% lebih mahal untuk pakaian dewasa
* 13% lebih mahal untuk produk perawatan pribadi
* 8% lebih mahal untuk produk perawatan kesehatan senior / rumah
Studi tersebut mengungkap sejumlah produk perempuan dan laki-laki yang sejenis dengan fungsi yang sama, namun harganya berbeda. Sebagai contoh, harga pisau cukur. Pisau cukur tanpa titanium bebas karat, tidak ada strip pelembab dan hanya memiliki pisau tunggal. Versi laki-laki berwarna biru dan versi perempuan warnanya pink. Hanya warna yang membedakan kedua produk tersebut, selebihnya sama persis. Namun, harga pisau cukur pink lebih mahal dibanding yang berwarna biru. Begitu juga dengan produk pakaian. Salah satu brand ternama tertangkap basah menerapkan pink tax dengan menetapkan harga yang lebih mahal untuk pakaian perempuan plus size (ukuran besar) namun tidak untuk pakaian laki-laki. Sebagai contoh, jeans perempuan plus size harganya lebih mahal USD 12-15 dibanding ukuran standar. Sementara tidak ada perbedaan harga antara jeans laki-laki plus size dan ukuran biasa.
Meski hasil studi tersebut dirilis pada 2015 silam, kontroversi terkait pink tax masih berlangsung hingga kini. Ada banyak penelitian terkait yang dilakukan di Amerika, juga menemukan bahwa secara keseluruhan perempuan memang membayar lebih mahal 42% dari laki-laki sepanjang hidupnya. Selain itu, ada juga biaya tambahan yang senilai lebih dari USD 1.300 yang harus dikeluarkan perempuan per tahun. Namun, biaya tersebut tidak bisa disertakan dalam dana pensiun. Padahal, faktanya perempuan hidup lebih lama dibanding laki-laki, jadi perempuan jelas lebih membutuhkan uang pensiun tersebut.
Kontroversi pink tax ini pun mendorong sejumlah negara bagian AS untuk mengajukan penghapusan pajak gender, termasuk salah satunya New York.
Menurut Gubernur New York Andrew Cuomo, proposal penghapusan pink tax akan menjadi agenda di 2020 ini. Dengan adanya proposal penghapusan pink tax, maka dimungkinkan adanya aturan yang melarang penetapan harga berdasarkan gender untuk produk-produk perempuan dan laki-laki yang serupa. Penghapusan pink tax diharapkan dapat menghilangkan diskriminasi pada perempuan.
Pink Tax "Bukan Pajak"
Terlepas namanya adalah pink tax, pajak gender ini sebenarnya bukan pajak dalam arti sebenarnya atau pajak secara literal. Mengutip taxback.com, ada kesalahpahaman yang kerap terjadi jika berbicara soal pink tax. Kebanyakan orang beranggapan, pink tax adalah pajak yang sah sehingga merupakan kebijakan pemerintah. Kenyataannya, pink tax bukan retribusi resmi untuk produk-produk perempuan. Melainkan, biaya ekstra yang ditambahkan retailer, produsen dan merek ke produk yang dipasarkan untuk perempuan.
Namun, tidak juga berarti bahwa tidak ada peran pemerintah dalam pengenaan pajak gender ini. Ada beberapa produk perempuan yang dikenai pajak penjualan karena masuk dalam kategori barang mewah yaitu pembalut atau dikenal dengan tampon tax. Persoalan tampon tax ini bahkan lebih pelik lagi dibanding pink tax. Wacana penghapusan tampon tax ini lebih masif di berbagai negara ketimbang pink tax. Di Amerika sendiri, setidaknya sudah ada 32 negara bagian yang resmi menghapus tampon tax. Intinya, terkait pemerintah atau tidak, keberadaan pink tax ini tampaknya cukup melukai rasa keadilan terhadap kesetaraan gender.
Manipulasi Harga
Ternyata banyak perempuan yang tidak sadar akan keberadaan pink tax. Karena mereka juga tidak pernah ambil pusing untuk membandingkan harga produk barang maupun jasa bagi perempuan dan laki-laki. Inilah yang dimanfaatkan industri hingga mereka berani mencantumkan harga yang lebih mahal untuk produk perempuan. Konsumen perempuan telah dikondisikan untuk mengabaikan perbedaan harga antara produk mereka dan produk laki-laki untuk jenis barang yang sama.
Ketika suatu produk dilabeli sebagai "untuk laki-laki," hal ini menciptakan hambatan pembelian implisit untuk perempuan. Mereka memandang produk-produk ini "bukan untuk saya". Selain itu, produk-produk gender terkadang disimpan secara terpisah untuk mengaburkan perbedaan harga.
Industri juga meyakini bahwa perempuan cenderung kurang sensitif terhadap harga sehingga bersedia membayar lebih. Produsen dan retailer cukup tahu, jika mereka mencoba menaikkan harga pisau cukur atau shampoo, laki-laki pasti akan memilih berbelanja di tempat lain atau berhemat dengan tidak membeli produk tersebut. Sementara perempuan, tetap rela membayar harga yang lebih tinggi.
Memang, harga barang ditentukan dari biaya produksi dikombinasikan dengan apa yang bersedia dibayar oleh pelanggan. Dan terkadang perusahaan memang harus mengeluarkan dana produksi yang lebih banyak untuk pengembangan produk-produk perempuan. Namun, perusahaan-perusahaan ini juga menghabiskan banyak uang untuk melakukan pemasaran agar produk yang menarget kaum hawa menjadi lebih menarik--tanpa sadar konsumen perempuan membayar lebih dibanding laki-laki, untuk sebuah produk yang sama. Sayangnya, mereka berhasil. (Ken/Ags)
Disclaimer! Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja.


